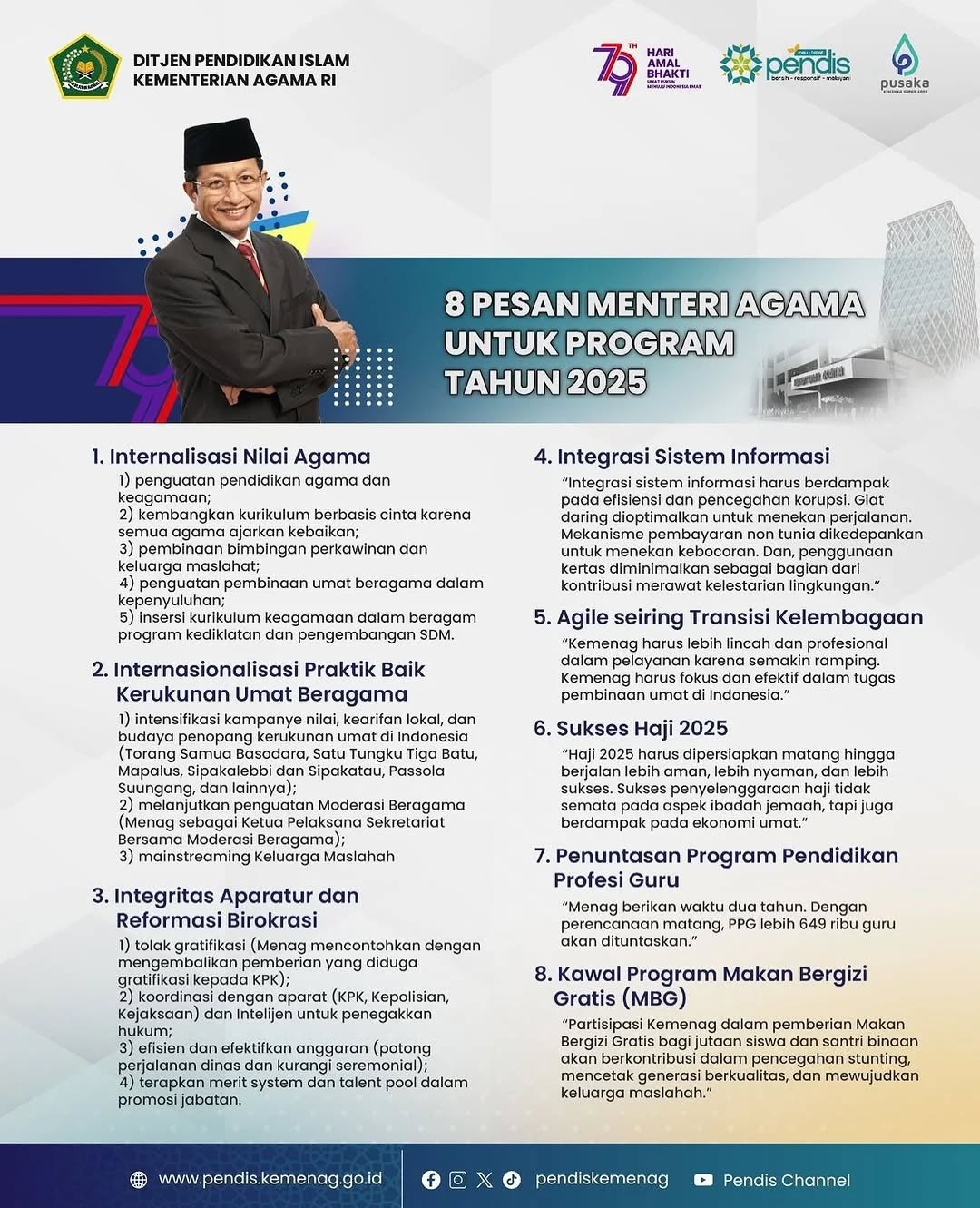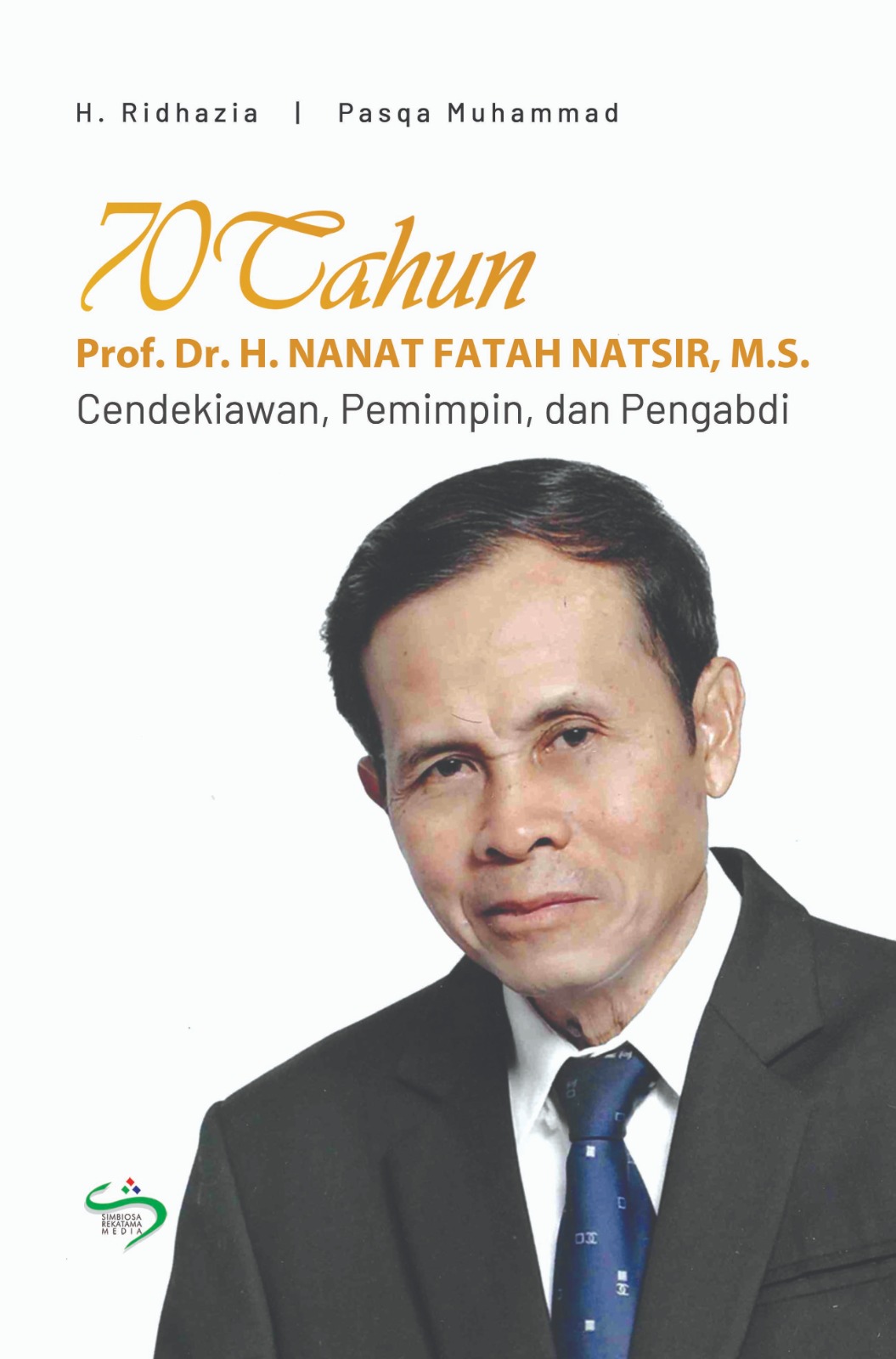BERITA UIN
Sumbangan Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi bagi Masa Depan Hukum Islam

Yusuf al-Qaradawi, yang dikenal di tanah air dengan Yusuf Qardawi, adalah ulama kontemporer, yang sangat ditunggu-tunggu fatwanya oleh masyarakat muslim internasional. Ulama kelahiran Mesir tahun 1926 dan masih hidup, adalah ulama yang sangat produktif, ia telah menulis berbagai hal tentang Islam, yang tercatat lebih dari 20 buah judul buku. Yang mengesankan dari Dewan Penyantun Pusat Studi Keislaman di Universitas Oxford dan sejumlah organisasi Islam Internasional, baik yang berpusat di Timur Tengah, maupun di Eropa dan Amerika Serikat saat ini, adalah fatwa-fatwa beliau yang mengisyaratkan pentingnya mengkaji kembali fatwa-fatwa ulama terdahulu demi menyelaraskan dengan kebutuhan hidup umat hari ini.
Dalam fatwa kontemporernya, terutama terkait dengan perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, al-Qaradawi memberi ilustrasi pemikiran bahwa prestasi ilmiah yang diraih dalam dunia sains dan teknologi pada abad ini telah berkembang dengan pesat di setiap level. Kegemilangan-kegemilangan ini terealisasi justru ketika sebagian orang mengira bahwa hal itu merupakan sesuatu yang mustahil.
Di antara keberhasilan-keberhasilan penting yang diraih oleh manusia adalah terciptanya radio, yang kehadirannya mencengangkan orang. Bagaimana mungkin seseorang dapat mendengar suara orang lain, sementara antara mereka dipisahkan oleh lautan, pegunungan, lembah, padang pasir, yang jaraknya ribuan kilo meter.
Ketercengangan mereka semakin bertambah dengan terciptanya televisi, yang suaranya bisa didengarkan sekaligus dilihat gambar pengucapnya. Pada mulanya, televisi hadir dengan layar hitam putih, lalu berkembang menjadi berwarna. Setelah itu dilanjutkan dengan hadirnya perangkat satelit di dunia pertelevisian.
Di dunia komunikasi, saluran-saluran komunikasi (telefon) di abad ini tidak lagi menggunakan kabel, sebagaimana sebelumnya. Umat manusia kini melihat handpone yang bisa dibawa ke mana-mana, ukurannya semakin mengecil sampai batas terkecil, dengan memberikan lebih banyak pelayanan. Bahkan terdapat pula telefon yang pemakainya bisa melihat wajah teman bicaranya.
Manusia telah mampu berkomunikasi melalui teleks dan faksimile yang tak henti-hentinya berkembang. Ini semua merupakan salah satu dari tanda-tanda kebe-saran Allah SWT. Selain itu masih banyak lagi ragam keajaiban komunikasi, hingga disebut sebagai “revolusi komunikasi”. Dalam dunia komunikasi ini, terakhir lahir suatu jaringan komunikasi yang dinamakan dengan internet.
Dalam dunia kedokteran, pun terjadi kemajuan yang tidak kalah pesat. Khususnya dalam ilmu operasi dan bedah, lebih spesifik lagi pada teknik operasi hati dan mata yang telah menggunakan laser. Tidak hanya itu, bidang kedokteran sudah mampu melakukan transplantasi anggota tubuh, dari mulai ginjal, jantung, hati, kornea, hingga anggota tubuh lainnya.
Ilmu kedokteran juga menemukan untuk pertama kalinya bayi tabung dan penyakit AIDS.
Adapun di dunia obat-obatan, telah tercipta plasma darah dan injeksi yang banyak membantu menyembuhkan orang dari berbagai penyakit. Selain itu ada juga jenis obat-obatan yang sekadar digunakan untuk kekebalan tubuh, seperti untuk penyakit cacar.
Dunia obat-obatan telah mampu menciptakan pil KB dan pinicilin. Pinicilin adalah suatu obat antibiotik yang dalam perkembangannya mempunyai pengaruh terhadap kemajuan di bidang operasi bedah.
Demikian pula telah diciptakan jenis obat peredam rasa sakit, seperti aspirin dan sejenisnya, juga penenang rasa sakit perut (mulas) dan tulang.
Penemuan ini telah menciptakan sebuah revolusi global di dunia perindustrian dan pola hidup secara umum. Dengan komputer itulah pesawat-pesawat beterbangan, roket-roket berluncuran, satelit-satelit buatan terus berputar, dan pesawat luar angkasa melesat jauh ke langit, hingga urusan kehidupan hampir-hampir tidak bisa lepas dari revolusi elektronik, dan sampai anak-anak pun tidak ketinggalan turut menikmatinya. Kini, sistem pendidikan modern telah mewajibkan pengajaran komputer pada sekolah-sekolah dasar.
Di samping revolusi teknologi, astronomi, komunikasi, kedokteran, elektro-nik, terdapat pula revolusi lain yaitu revolusi biologi. Revolusi ini meliputi rekayasa genetika dan penentuan janin. Dengan revolusi biologi ini, mereka mampu menen-tukan apakah jenis janin yang berada dalam kandungan itu laki-laki ataukah perem-puan. Barangkali juga mampu menentukan bentuk dan wajahnya, berkulit hitamkah atau putih, rambutnya lurus atau ikal, kedua matanya biru atau hitam, dan sebagainya, sampa-sampai sebagian orang menyebutnya sebagai “bayi sesuai katalog”.
Puncak prestasi dalam bidang biologi ini berakhir pada “kloning hewan”, sebagaimana pernah dilakukan pada seekor biri-biri betina yang kemudian terkenal dengan nama Dolly. Peristiwa ini menjadi menakutkan jika terus berkembang ke kloning manusia. Inilah yang diperingatkan oleh para pakar agama, akhlak, sosial, dan hukum, karena praktek kloning itu membawa madarat dan bahaya.
Masih ada lagi revolusi lain, yang dinamakan “revolusi informasi”. Kita sekarang berada pada era “ledakan ilmu pengetahuan” di mana kuantitas pengetahuan yang kita terima menjadi tak terhitung kadarnya yang pada akhirnya mengharuskan kita untuk membuat bab-bab dan daftar isi yang sesuai dengan bidangnya.
Revolusi-revolusi ini telah menghasilkan berbagai macam hal yang menguntungkan: kesejahteraan hidup, efesiensi tempat dan waktu, memperpendek jarak, penghematan waktu dan tenaga, kemudahan transpontasi, cara mendapatkan kenyamanan seperti AC di musim panas, penghangat ruangan di musim dingin, pendingin dan pemanas air sesuai kebutuhan, hadirnya mesin cuci dan oven elektrik, microwave, mesin-mesin pembersih, dan sebagainya.
Kini dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini tak satu pun orang yang mengingkari bahwa adanya abad modern dengan kepesatan teknologinya itu berakibat telah terjadinya perubahan sosial bagi kehidupan umat manusia, tak terkecuali umat Islam, baik di bidang kemasyarakatan, ekonomi, politik dan budaya. Semua kemajuan itu justru menantang setiap pemikir muslim untuk mengkaji ulang terhadap khazanah pemikiran klasik yang barangkali telah tidak sesuai dengan tuntutan kondisi, karena itu pada saat yang sama diperlukan memilih sebagian yang pada zamannya dianggap tidak kuat atau bahkan harus diabaikan, dengan kata lain sebagian dari khazanah pemikiran itu harus mengikuti keadaan.
Seiring dengan kenyataan adanya perubahan sosial sebagai akibat kemajuan zaman, muncul permintaan fatwa Islam dari masyarakat luas dalam menghadapi persoalan yang sedang dihadapi masyarakat modern. Permintaan fatwa itu menurut al-Qaradawi, bukanlah suatu tindakan main-main dan mengecilkan Islam. Dalam faktanya, sebagian orang menginginkan petunjuk Islam untuk selanjutnya diamalkan dalam kehidupan kesehariannya sesuai dengan fatwa yang diterimanya, misalnya mereka yang bergelut dalam dunia perbankan, asuransi, bisnis saham, transportasi, kesehatan, mengenai zakat dan lain sebagainya.
Pandangan al-Qaradawi di atas memang ada relevansinya dengan kenyataan adanya kebutuhan pemikiran baru yang betul-betul berbeda dengan ketentuan pemikiran fiqh yang lama. Atau sekurang-kurangnya adanya penafsiran baru atas teks-teks Shari’at karena atas pertimbangan adanya ‘illat hukum yang telah berubah, ‘illat telah hilang sama sekali, adanya ‘illat baru, atau adanya pertimbangan yang lebih rasional. Maka dengan dasar-dasar seperti itu, pemahaman hukum atau fatwa hukum yang baru itu bisa lebih variatif, tidak hanya satu pilihan saja, yang memungkinkan semuanya bisa dibenarkan dan sesuai dengan maqasid al-Shari’at.
Berbagai persoalan yang perlu mendapat pengujian kembali atas fatwa masa lalu maupun persoalan baru yang memerlukan fatwa-fatwa baru, sebagaimana mengacu pada pemikiran al-Qaradawi di atas antara lain:
1. Mengabaikan rukhsah karena tidak diperlukan lagi.
Aturan tentang rukhsah (keringanan) yang ditetapkan Allah bagi musafir, seperti salat bisa di-jama’ dan qasar, serta wudhu’ bisa diganti dengan tayamum. Rukhsah ini berlaku jika memang perjalanan itu ‘illat-nya seperti perjalanan yang terjadi dizaman al-Qur’an turun, yang penuh dengan kesulitan. Jika perjalanan yang dilakukan oleh manusia modern dewasa ini yang dalam faktanya penuh dengan kemudahan, bisa sambil tidur dan setiap saat bisa istirahat di setiap tempat, maka tampak tidak ada ‘illat yang bernama kesulitan itu, dan dengan begitu seharusnya hukumnya kembali ke asal.
Jika bepergian dianggap sebagai ‘illat hukum, baik bepergian yang menyenangkan atau penuh kesulitan, sehingga bisa diberlakukan hukum rukhsah, maka tindakan ini dipandang tidak adil dan tidak rasional. Sebab sosial zaman lalu berbeda dengan sekarang. Zaman dulu bepergian itu identik dengan adanya unsur kesulitan, sementara sekarang, zaman telah jauh berubah.
Demikian pula rukhsah bagi wanita yang melahirkan di mana pada zaman Rasul ditetapkan dan dibolehkan untuk meninggalkan salat selama 40 hari. Jika ketetapan ini terus berlaku, maka tampaknya ketetapan ini tidak rasional, sebab penanganan kelahiran dewasa ini jauh lebih maju dibanding pada zaman Nabi.
2. Peninjauan kembali ketentuan membayar zakat fitrah.
Masyarakat muslim Indonesia secara tradisi, yang mungkin merupakan fatwa ulama tempo dulu, membayar zakat fitrah dengan ukuran beras, sebagai Qiyas dari makanan pokok gandum. Pengiyasan seperti itu dipandang kurang tepat karena yang dinyatakan dalam teks Shari’at zakat fitrah itu terlebih dahulu disebutkan dengan kurma, seperti Hadith Nabi menyatakan:
“Zakat fitrah itu satu sa’ kurma, atau satu sa’sha’ir dari setiap kepala, atau satu sa’ bur atau gandum antara dua orang…” Riwayat Ahmad dan Abu Dawud dari
Abd Allah bin Ta’labah.
Bahkan Hadith-hadith tentang zakat fitrah yang diriwayatkan dan dijadikan dasar hukum oleh Imam al-Shafi’i dalam memberikan fatwanya, tidak menyebutkan bahwa zakat fitrah itu dengan gandum, melainkan dengan makanan secara umum (ta’am).
Zakat fitrah dengan memakai ukuran kurma seperti dijelaskan dalam Hadith di atas, jelas akan membedakan nilai harganya, jika dibanding dengan memakai ukuran gandum. Harga kurma yang standar, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah harganya, misalnya yang dijual di pasar-pasar di Indonesia yaitu: 40.000/kg x 2,5 kg (1 sa’) = 100.000/perorang, untuk setiap zakat fitrah. Sebaliknya, jika bersandar pada ukuran beras (gandum), adalah: 6.000/kg x 2,5 (1 sa’) = 15.000/perorang, untuk setiap zakat fitrah. Perbedaan ini jauh sekali, dan tentunya memiliki kadar paling rendah nilai ‘ubudiyah-nya.
Alasan para ulama atas pengiyasan kepada beras dari gandum itu karena dipandang sebagai makanan pokok. Hal ini juga dipandang tidak tepat, sekalipun beras dan gandum memiliki kesamaan sebagai makanan pokok yang dapat mengenyangkan perut, tetapi makanan ini memerlukan makanan pendamping lainnya ketika dikonsumsi seperti lauk pauk dan sayuran, yang tentunya penyediaannya memerlukan biaya. Sementara jika diqiyaskan kepada kurma, yang sesungguhnya disebutkan paling awal dalam teks Hadith tersebut, maka makan kurma tidak memer-lukan makanan pendamping lainnya, seperti ikan dan sayuran, ia hanya cukup ditemani oleh segelas air. Demikian pula nilai gizi yang dikandung kurma jauh lebih tinggi dibanding dengan yang terdapat dalam gandum.
Jadi, zakat fitrah dengan memakai ukuran kurma jauh lebih mendekatkan pada maqasid al-Shari’at zakat fitrah itu sendiri dibanding dengan zakat dengan memakai ukuran gandum. Apalagi sekarang berzakat fitrah dengan memakai ukuran kurma dan gandum sama-sama dalam praktiknya bisa dinilaikan kepada harga kedunya (diuangkan). Bukan dengan kedua jenis makanan itu sendiri.
3. Peninjauan kembali ketentuan ‘iddah wanita yang dicerai.
Para ulama dengan segala otoritas yang dimilikinya telah menetapkan bahwa masa menunggu (‘iddah) bagi wanita yang dicerai suaminya adalah 3 bulan. Ketetapan ini berdasarkan tafsiran dari kata quru’, yang diartikan dengan tiga kali suci dari mestruasi (haid). Kata tersebut dinyatakan ayat: “Wanita-wanita yang dicerai hendaklah menahan din (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya…” (Q.S. al-Baqarah, 2: 288).
Padahal kata quru’ bersifat ambigus atau mushtarakah (mempunyai arti lebih dan satu). Kata tersebut dapat berarti menstruasi (haid) dan dapat pula berarti dalam keadaan suci (tuhr). ‘Umar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib, ibn Mas’ud, dan Abu Musa al-Ash’ari, menafsirkan kata “aqra’“, yakni bentuk tunggal, mufrad dan kata quru’ itu dengan tafsiran menstruasi (haid). Tafsiran ini dipegangi pula oleh Sa’id al-Musayyab, Ata’, dan beberapa kelompok tabi’in serta sejumlah ahli hukum. Sementara itu, ‘Aishah, Zayd ibn Tabit dan Ibnu ‘Umar diriwayatkan bahwa mereka menafsirkan kata “aqra’” yang terdapat pada ayat di atas dengan tafsiran masa suci serta di antara menstruasi (athar).
Perbedaan tafsiran mengenai ayat hukum di atas menyebabkan perbedaan dalam penentuan ‘iddah bagi wanita yang dicerai. Menurut tafsiran pertama masa menunggu bagi wanita yang dicerai (‘iddah) itu adalah setelah selesai menstruasi ketiga. Sedangkan menurut tafsiran kedua, ‘iddah selesai dengan dimulainya menstruasi ketiga.
Jadi, tafsiran pertama mengharuskan wanita menyelesaikan masa ‘iddah-nya itu selama tiga bulan penuh. Sedangkan tafsiran kedua menyatakan tidak harus selama tiga bulan penuh, yakni cukup pada waktu dimulai mestruasi ketiga saja. Bahkan Hadith da’if menyatakan bahwa ‘iddah wanita yang dicerai itu cukup dua kali mestruasi saja.
Ketentuan ‘iddah ini ‘illat hukumnya untuk mengetahui apakah wanita yang dicerai itu sedang mengandung janin dari suaminya atau tidak dalam keadaan mengan-dung. Jika diketahui sedang mengandung, ‘Umar bin Khattab melarang suami men-ceraikan istrinya dalam keadaan mengandung. Jika pun harus terpaksa bercerai, maka ‘iddah wanita yang dicerai dalam keadaan mengandung itu adalah hingga melahirkan.
‘illat tersebut sesungguhnya sudah bisa diketahui melalui bantuan teknologi kedokteran atau alat USG, apakah wanita itu mengandung atau tidak mengandung, dengan tidak harus menunggu hingga tiga kali quru’. Namun hikmah dibalik ketentuan itu, bisa jadi Tuhan masih memberi kesempatan kepada pasangan yang bercerai itu untuk bisa kembali lagi sebagai suami istri sebagaimana semula. Namun jika perceraian itu telah tiga kali dilakukan di mana telah terjadi talaq ba’in, yang tentunya tidak bisa kembali menikah, maka dengan bantuan teknologi kedokteran atau alat USG untuk mengetahui apakah istri yang dicerai itu dalam keadaan hamil atau tidak hamil, sepertinya tidak perlu menunggu hingga tiga kali mestruasi, melainkan cukup satu kali saja untuk membuktikan kebenaran diagnosis kedokteran yang menyatakan ketidakhamilan perempuan yang dicerai itu. Tentu kecanggihan alat kedokteran ini akan berhadapan dengan teks ayat yang menyatakan tiga kali quru’ seperti di atas, yang sesungguhnya ‘illat hukumnya untuk mengetahui keadaan rahim wanita yang dicerai itu apakah dalam keadaan hamil atau tidak hamil.
Dalam fatwa tersebut terlihat bahwa al-Qaradawi mendukung kemajuan teknologi kedokteran. Karena itu seharusnya pula ketetapan tentang masa ‘iddah wanita yang dicerai itu pun yang ‘illat-nya untuk mengetahui hamil dan tidaknya wanita yang dicerai itu tidak bisa secara mutlak ditentukan harus selama tiga kali haid. Karena rahasia rahim wanita yang menjadi ‘illat bagi masa ‘iddah telah diketahui secara gamlang oleh teknologi kedokteran. Lagi pula bagi manusia modern sekarang yang lebih rasional, dalam memutuskan untuk bercerai biasanya didahului dengan proses pisah ranjang yang berbulan-bulan, yang tentunya tidak melakukan persetubuhan (junub) antara pasangan itu, yang bisa menyebabkan kehamilan.
Pemikiran-pemikiran al-Qaradawi tersebut di atas merupakan wacana bagi reformasi pemahaman di bidang hukum Islam di masa mendatang, yang lebih arif dan bijaksana sebagai respon positif atas berbagai kemajuan teknologi yang telah dicapai manusia modern, terutama yang dialami dunia Barat dewasa ini, yang imbasnya tentu dialami pula oleh masyarakat muslim di mana pun berada.
LOGIKA HUKUM ISLAM AL-QARADAWI BAGI BOLEHNYA PEREMPUAN MENJADI PEMIMPIN
Berbagai persoalan kehidupan yang diajukan dan ditanyakan kepada al- Qaradawi dalam berbagai kesempatan, baik di saat beliau memberikan ceramah, menyampaikan seminar, mengisi acara di televisi dan radio maupun pertanyaan yang disampaikan melalui tulisan yang dimuat di surat kabar atau majalah diuraikan secara luas, cermat, bijaksana, tidak hanya disertai argumentasi yang bersumber pada dalil naqli (al-Qur’an dan al-Sunnah) dan rasio, namun disertai dengan hikmah dan maksud yang terkandung di dalamnya. Pemberian jawaban dengan disertai hikmah inilah yang menjadi salah satu keunggulan dan ciri khas al-Qaradawi dalam memberikan fatwa-fatwanya dibandingkan ulama lainnya.
Seiring dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan kepadanya mulai pertanyaan yang berhubungan dengan al-Qur’an al-Karim dan tafsirnya, seputar Hadith nabawi, masalah aqidah dan perkara ghaib, masalah taharah, dan salat, zakat, puasa, haji dan umrah, masalah yang berhubungan dengan peringatan hari-hari besar, sumpah, wanita dan keluarga, hubungan sosial dan bidang politik pemerintahan sampai masalah-masalah kontemporer yang terkait erat dengan bidang kedokteran dan ilmu pengetahuan telah membuat namanya mencuat dan dikenal di penjuru dunia sebagai salah seorang pakar hukum Islam dan mujtahid abad ke-21.
Sebagai upaya untuk memperluas fatwa-fatwanya dan produk hukumnya serta atas saran dan usulan pemirsa dan pendengar di radio dan televisi, al-Qaradawi menghimpun fatwanya dalam tiga jilid yang diberi nama Min Hadyi al-Islam Fatawa Mu’asirah yang membuat berbagai persoalan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Judul tersebut merupakan nama acara dakwah di sebuah stasiun televisi yang dipandu al-Qaradawi.
Salah satu pembahasan yang tercakup dalam fatwa-fatwa tersebut adalah pembahasan yang berkaitan dengan problematika kontemporer di bidang sosial budaya, sosial ekonomi, kedokteran dan ilmu pengetahuan serta persoalan politik (siyasah). Dalam menjawab persoalan-persoalan tersebut, al-Qaradawi menggunakan metode Ijtihad Intiqaiy dan Inshaiy. Ijtihad Intiqaiy adalah memilih suatu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fikih Islam yang dengan fatwa dan putusan hukum. Sedangkan ijtihad Inshaiy adalah pengambilan istinbat hukum dari suatu persoalan yang baru, yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu, baik istinbat itu menyangkut masalah lama (dengan ’illat baru) atau masa-lah yang betul-betul baru.
Dalam buku: Min Hadyi al-Islam Fatawa Mu’asirah dan al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, al-Qaradawi dalam kedua bukunya tersebut telah memberikan fatwa sebanyak 619 buah tema. 422 buah tema terdapat dalam kitab Min Hadyi al-Islam Fatawa Mu’asirah. Sedangkan dalam buku al-Halal wa al-Haram al-Qaradawi telah membahas 197 tema, di luar pembahasan tentang prinsip halal dan haram dalam Shari’at Islam.
Dari sekian banyak fatwa yang paling menarik disimak dari logika-logika hukum Islam yang dikemukakan al-Qaradawi adalah fatwa tentang bolehnya perempuan menjadi pemimpin, baik menjadi presiden, gubernur, maupun menjadi bupati dan walikota. Fatwa ini menjadi penting di tanah air mengingat adanya pro kontra diantara para ulama tentang persoalan tersebut.
Kebanyakan kyai, ulama dan fuqaha termasuk di Indonesia melarang wanita menjadi seorang presiden, gubernur, bupati dan walikota, berdasarkan firman Allah SWT: ”al-Rijalu qawwamÅ«na ’ala al-nisa” (QS. Al-Nisa: 34), laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Karena itu hanya laki-laki yang berhak menjadi pemimpin. Pemahaman ini dikuatkan lagi dengan sebuah Hadith sahih, ”lan yufliha qaumun wallau amrahum imra’atan, tidak akan bahagia kaum yang menyerahkan urusannya (mengangkat penguasa, presiden) seorang wanita.
Dalam persoalan di atas, al-Qaradawi mengulasnya ketika ada sebuah perta-nyaan mengenai hukum seorang wanita menjadi anggota parlemen (legislatif) yang kemudian dijawab oleh al-Qaradawi secara luas yang merembet pada persoalan hukum seorang wanita menjadi presiden dalam sebuah negara modern yang menerapkan sistem demokrasi sebagaimana diterapkan hampir di seluruh negara termasuk negara-negara muslim.
Dalam menjawab persoalan ini, al-Qaradawi berpendapat untuk mengha-silkan pemahaman yang tepat, Hadith tersebut harus dikaitkan dengan sejarah dan konteks sosial yang dituju oleh Hadith. Karena fakta sejarah menunjukan Hadith tersebut diucapkan nabi terkait dengan peristiwa suksesi di Persia yang menganut pemerintahan monarki yang ada di ambang kehancuran. Kemudian diperintah oleh seorang putri kaisar, walaupun dikalangan mereka sebenarnya banyak orang yang lebih mampu dan pantas. Dan sebagaimana kita ketahui, sistem monarki tidak mengenal musyawarah, tidak menghormati pendapat yang berlawanan dan tidak terjalinnya hubungan yang seimbang dan sepadan antara rakyat dan penguasa.
Oleh karena itu, al-Qaradawi berpendapat dalam memahami Hadith ini terasa tepat menggunakan kaidah: ”kekhususan sebab” bukan kaidah, ”keumuman lafaz”. Sehingga Hadith ini ditujukan spesifik kepada ratu Kisra di Persia, karena seandainya sistem pemerintahan di Persia berdasar musyawarah dan seandainya wanita yang menduduki singgasana kepemimpinan mereka seperti Golda Meir yang memimpin Israel, atau Margaret Tatcher di Inggris, Indira Gandhi di India, mungkin komentar nabi akan berbeda.
Kemudian lanjut al-Qaradawi, apabila Hadith tersebut dipahami menurut umumnya akan tampak bertentangan dengan ayat: ”Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita [Ratu Balqis di zaman Sulaiman] yang memerintah mereka, dan Dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.” Q.S. al-Naml, 27: 23, tentang Ratu Balqis yang memerintah kerajaan Saba’iyah pada masa Nabi Sulaiman. Menghadapi masalah ini, al-Qaradawi berpendapat harus mengembalikan pada dalil-dalil kulli, yang menunjukkan hubungan antara pria dan wanita yang sama dalam beribadat kepada Allah, menegakkan agama, melaksanakan kewajiban, menjauhi larangan, menghormati batas-batas-Nya, berdakwah untuk agama-Nya, dan melakukan amar ma’ruf nahi munkar sesuai dengan Firman Allah dalam QS. Ali Imran, 3: 195, Q.S. al-Nahl, 16: 97. Demikian juga Hadith Nabi, kedudukan wanita yang seimbang dengan laki-laki.
Berdasarkan ketentuan di atas, menurut al-Qaradawi, seorang wanita boleh saja berkarir di dalam atau di luar rumahnya, dengan syarat tidak melanggar kode etik kesopanan yang diajarkan Shari’at. Tidak mempertontonkan perhiasan dan kecantikan kepada orang lain, sehingga mengumbar nafsu, tidak melakukan pergaulan bebas, tidak duduk berdua antara seorang wanita dengan seorang laki-laki yang bukan muhrim.
Menurut al-Qaradawi, dalam tataran historis sangat banyak aktivitas yang dijalankan oleh kaum wanita diberbagai lapangan yang mulia dan terhormat, baik di tingkat lokal, nasional dan internasional, meski demikian diakui di tempat yang berbeda ada juga kiprah maum wanita yang rendah dan amoral. Dalam sejarah Islam, misalkan ‘Umar bin Khattab pernah mengangkat al-Shifa binti Abdullah al-Adawiyah sebagai kepala pasar untuk melakukan perhitungan dan pengawasan dan ini salah satu bentuk dari kekuasaan secara umum. Sementara, pada masa modern, al-Qaradawi menyebut kepemimpian wanita yang sukses antara lain Tatcher di Inggris, Indira di India, atau Golda Meir di tanah pendudukan Palestina.
Dan perlu dicatat, menurut al-Qaradawi, pengharaman ulama atas kepemim-pinan wanita konteksnya berlaku pada kepemimpinan Islam yang menerapkan sistem khilafah yang bersifat sentralistik dan bersifat umum (mutlak). Sementara di zaman sekarang yang menggunakan sistem demokrasi, presiden hanyalah salah satu bagian kekuasaan (kekuasaan eksekutif) di mana ada kekuasaan yang seimbang dan atau lebih tinggi kedaulatannya di bandingkan presiden yakni kekuasaan legislatif dan yudikatif sehingga adanya chek and balance. Maka dengan perkembangan struktur kekuasaan ini, al-Qaradawi berpendapat, kalaulah wanita ada yang menjadi presiden yang dipilih secara demokratis maka tidaklah menjadi soal. Asalkan memang wanita itu cakap dan layak.
Karena itu, sudah sepantasnya penolakan terhadap presiden perempuan, bukan lagi didasarkan jenis kelaminnya, melainkan didasarkan pada kemampuannya. Sehingga tidak lagi membedabedakan jenis kelaminnya; laki-laki atau perempuan. Perempuan tidak lagi dipandang lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk memimpin.
Pandangan al-Qaradawi di atas mengingatkan pada sikap ‘Umar bin Khattab yang selalu memegang makna ayat ketimbang lafaznya, seperti diceritakan dalam sejarah bahwa suatu ketika ‘Umar menerima suatu surat dari Hudaifah bin al-Yaman, yang isinya menceritakan bahwa ia telah kawin dengan seorang wanita Yahudi di kota Mada’in, ketika Hudaifah meminta pendapat. Maka ‘Umar, dalam surat jawabannya memberi peringatan keras antara lain menyatakan: ”Kuharap engkau tidak akan melepaskan surat ini sampai dia (wanita Yahudi) itu engkau lepaskan. Sebab aku khawatir kaum muslimin akan mengikuti jejakmu, lalu mereka mengutamakan para wanita ahli kitab (yang dilindungi) karena kecantikan mereka. Hal ini sudah cukup sebagai bencana bagi para wanita muslimat.
Terlihat di situ bahwa ‘Umar telah keluar dari pemahaman secara lafaziyah tentang ayat yang membolehkan menikahi wanita ahli kitab (QS. Al-Maidah, 5:5).
Bahkan ‘Umar dalam beberapa kasus lain keluar dari teks ayat dan memahaminya melalui makna ayat maupun makna dari Sunnah Nabi. Misalnya tentang kasus pencurian yang pencurinya sengaja dilepas oleh ‘Umar dan tidak dihukuminya. Demikian pula ‘Umar melepas penguasaan tanah Khaibar dari tangan para tentara Islam, yang berjasa menguasai tanah tersebut, sebagaimana dulu ditetapkan oleh Rasul. Karena ‘Umar khawatir tanah tersebut setelah para tentara meninggal, dianggap sebagai warisan oleh anak keturunan mereka. Namun ‘Umar mengganti atas penguasaan tanah Khaibar itu dengan gaji yang diterima oleh para tentara tiap bulannya.
Konsep pemahaman ayat di atas yang dilakukan oleh ‘Umar, juga terlihat dalam sikap al-Qaradawi dalam fatwa tentang kebolehan perempuan menjadi pemim-pin (presiden) selama memenuhi berbagai persyaratan yang ada, di mana masalah penarikan atau pengangkatan makna umum (generalisasi) suatu nilai hukum akan menyangkut masalah penafsiran dan kemampuan memahami lebih mendalam inti pesan yang dikandungnya. Dan karena kemampuan tersebut dapat berbeda-beda antara berbagai pribadi, maka hasilnya pun dapat berbeda-beda pula. ‘Umar menun-jukkan bahwa yang dituju oleh hukum ialah makna atau pesan yang dikandungnya. Kaidah ini terkenal bahwa “Hukum ialah makna atau pesan yang dikandungnya.”
Jadi, apa yang dinyatakan oleh al-Qaradawi tentang kebolehan wanita mencalonkan diri sebagai pemimpin (presiden), adalah sesungguhnya merupakan pemaknaan substansial dari seluruh rangkaian ayat maupun Hadith Nabi yang secara tekstual menyatakan bahwa kepemimpinan ratu Kisra di Persia, dengan sistem pemerintahan monarki yang absolut dan tidak mengenal sistem musyawarah itu adalah haram. Dan letak keharaman itu sesungguhnya juga terhadap sistem pemerintahan yang absolut, dimana kekuasaan hanya ada di tangan seorang pemimpin (raja) saja tanpa terbagi sebagaimana dalam sistem demokrasi dewasa ini.
Jadi apa yang dinyatakan oleh al-Qaradawi bahwa wanita boleh menjadi pemimpin, hal itu bukan menentang ayat maupun sabda Nabi, tetapi al-Qaradawi di situ menempatkan kasus ini sebagaimana mestinya. Sekalipun fatwa ini dinilai kontroversi, tetapi itulah sesungguhnya substansi atau makna Hadith:
”Telah menceritakan kepada kami Utman bin Haitam, yang bersumber dari ’Auf dari Hasan dari Abi Bakrah, ia berkata: Sungguh bermanfaat bagi kami kalimat Allah yang saya dengar dari rasulullah pada hari-hari peperangan setelah hampir mendapatkan kemenangan bersama pasukan unta di mana saya berperang bersama mereka. Ia (Abi Bakrah) berkata pula: ketika Rasul dilapori bahwa sesungguhnya penduduk Farsi itu dipimpin oleh anak perempuan Qisra, maka Rasul berkata: Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan kekuasaan mereka kepada seorang perempuan” (Riwayat al-Bukhari).
Bahkan jika mau konsisten atas pemahaman secara tekstual, yakni melarang wanita menjadi pemimpin, maka bukan saja perempuan haram menjadi pemimpin, tetapi juga haram pula pemerintahan dengan memakai sistem monarki seperti yang dipraktikkan oleh penguasa Qisra di negeri Farsi, sebagaimana tersurat dalam Hadith tersebut. Namun sayangnya ulama yang melarang perempuan menjadi pemimpin, tidak terdengar suara fatwanya tentang haramnya pemerintahan yang menggunakan sistem monarki seperti kerajaan sebagaimana yang dipraktikan oleh penguasa Qisra di Farsi yang tertera dalam hadits itu.
Karena itu, secara umum pandangan-pandangan al-Qaradawi dalam banyak bukunya terlihat sangat moderat dan merupakan respon beliau atas tuntutan keadaan pada saat ini. Karenanya tidak salah jika para pengamat hukum Islam menggelari YÅ«suf al-Qaradawi sebagai ulama yang moderat dan tahu bagaimana ia harus memberikan fatwa sesuai dengan tuntutan ‘illat hukum yang ada dengan tanpa meninggalkan teks hukum itu sendiri. Dan tampaknya kebutuhan terhadap fatwa hukum yang demikian itu, sesungguhnya yang dibutuhkan oleh umat dewasa ini demi mengarungi kehidupan sosial yang lebih baik dewasa ini dan di masa yang akan datang. Karena setiap peristiwa sesungguhnya masih terkait dengan peristiwa masa lalu, baik langsung maupun tidak langsung.
Bandung, 10 Mei 2012.
Catatan:
1. Menggunakan transliterasi Arabinternasional, namun tanda baca panjangnya telah dihilangkan.